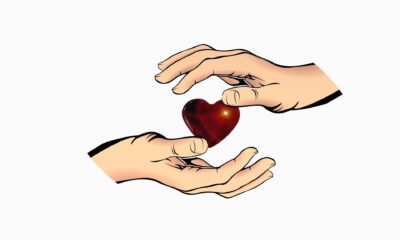Kolom
Jogja yang Tak Sesuai Ekspektasi dan Hal-hal Menyebalkan Lainnya

Oleh: Muhammad Husein Heikal
JOGJA sangat berbeda dengan yang saya bayangkan. Saya membayangkan Jogja sebagai kota keakraban, penuh persahabatan, keramahtamahan, dan––baiklah, itu terlalu klise. Membayangkan Jogja ialah membayangkan Basabasi, Mojok, pergaulan sastrawan, penulis partikelir, kafe penuh diskusi, UGM, mahasiswa kritis (pemikiran dan keuangannya), bedah buku, pameran, gelar budaya, serta sekerat candu dan jazz.
Walakin, nyatanya tak demikian, bahkan sejak perjalanan bermula.
Ceritanya begini. Saya sudah sebulan berada di Bandung dan kedatangan tamu seorang mantan penyair. Saat kami menjelajahi Lembang, saya mengatakan berencana ke Jogja. “Kapan?” sambutnya antusias. “Bebas!” Saya memang sedang tak punya ikatan tugas apapun. Singkat cerita diputuskanlah bahwa kami––saya, Ibu saya, sang mantan penyair, dan istrinya––berangkat malam itu juga.
Kami naik taksi online ke Terminal Cicaheum, dan terlambat mendapat bus Budiman (sebuah nama yang saya anggap sungguh jenaka). Bus yang bakal berangkat pukul 19.00 ialah Sugeng Rahayu (perpaduan nama dari dua jender). “170 ribu perorang, termasuk makan!” ujar agen tiket bus. Saya terkaget, tapi tetap berusaha calm down.
Bila dikomparasi dengan tarif bus di Sumatera Utara––daerah asal saya––tarif bus di Jawa termasuk mahal. Di Sumatera Utara tarif perjalanan untuk jarak 200 km (Medan-Tanjungbalai) hanya 45 ribu untuk bus kelas eksekutif dan 35 ribu untuk kelas ekonomi. Maka untuk jarak 400 km tarifnya sekitar 90-100 ribu. Itu artinya, margin dengan tarif bus eksekutif di Jawa untuk jarak 400 km (Bandung-Jogja jalur Selatan) berkisar 50-70 ribu.
“Kalau tak makan, berapa?” Ibu saya sinis. “155 ribu,” nadanya melemah. Entah karena kalah lantang dengan suara ibu saya, atau justru sedih akan kehilangan 15 ribu perorang. “Makannya prasmanan, Bu.” Ia mencoba meyakinkan. Akhirnya, kami memutuskan mengambil tiket termasuk makan. Maka berangkatlah bus tersebut lewat 10 menit dari waktu yang dijanjikan.
Sepanjang perjalanan, Ibu saya muntah kayak. Bau AC menyengat sekali. Sampai tiba jadwal berhenti, pukul 12 malam. Saya lapar sekali dan paling duluan mengambil makanan. Berbagai menu makanan berjejer. Perut saya kian meronta-ronta. Saya ambil nasi, sepotong ayam goreng, sepotong ikan, dan sepotong hati sapi. Saya serahkan tiket makan ke penjaga. “Tambah 16 ribu ya, Mas.” Lah, saya terlongo. “Tiket makan hanya buat satu menu plus sayur.” Perih hati saya merelakan ayam goreng dan ikan dipungutnya kembali.
Ternyata antrean di belakang saya sudah panjang. Agak malu saya, sekaligus kesal. Ketika hendak duduk, muncul sang mantan penyair (baiklah, namanya Mulya Jamil) dan istrinya yang baru dari toilet. Saya memanggil mereka dengan isyarat. “Cuma boleh ambil satu menu perorang,” saya mengingatkan. Mereka mengangguk. Tak berapa lama, Ibu saya muncul, dan saya pesankan hal yang sama plus kalimat, “Kuah semurnya ambil yang banyak.”
Baca juga: Things won’t change until we do
Selesai makan, bus kembali melaju. Kali ini istri Mulya yang muntah kayak. Parahnya kami kehabisan plastik. Terpaksalah tas bolu susu Lembang dikorbankan. Saya setengah mati bertahan agar tak muntah.
Kala fajar menyingsing mulailah memasuki wilayah DIY. Saya cek maps. 12 km menuju Terminal Giwangan. Beruntung ada warung kecil disudut terminal. Kami menenangkan diri dan serapan kecil-kecilan. Bagaimana tak saya sebut kecil-kecilan, biasanya kalau di Medan, setidaknya kami serapan lontong sayur lengkap dengan telor dan sambal teri atau nasi gurih. Kalau tak itu, ya mie balap dengan porsi melimpah.
Nah, di Giwangan ini yang ada hanyalah risol, roti, dan kue berbentuk bunga semacam bakpia. Yang tak mengenakkan ialah wajah penjualnya yang tak ramah. Terlihat jengkel dengan kedatangan kami. “Lah, salah kami apa?” Bahkan saat membayar pun seringainya tetap tak ramah.
Terus terang kami tak punya tujuan di Jogja. Tak ada saudara sama sekali. Saat di bus sempat saya chat Abul Muamar, alumni Magister Filsafat UGM dan Misbahul Munir, alumni Magister Ekonomi UII. Hanya dua orang ini yang saya tahu pernah di Jogja.
Satu menyarankan agar kami mencari kost di Kaliurang (aih, kali punya urang, bukan urang awak ni, saya pikir, manalah berani awak kesana). Satunya lagi menyarankan kami mencari kost di lorong-lorong Malioboro. Kami memutuskan mengikuti saran kedua.
Kami berjalan keluar terminal. Masing-masing menjinjing dua tas. Begitu tiba di luar terminal, terpampang spanduk larangan memesan ojek dan taksi online. Alamak! Tak beda dengan Bekasi, pikir saya. Maka berjalanlah kami seperti kura-kura menjauhi tawaran para tukang becak.
Malangnya saat memesan taksi online, baterai kehilangan daya. Kami melihat bus TransJogja lalu lalang. “Haltenya di mana?” pertanyaan kami membentur angin. Beruntung supir taksi online berhasil menemukan kami. Mulya duduk di depan, dengan penuh gaya, (mengingatkan saya pada tokoh Kucai Laskar Pelangi), mencoba membuka percakapan dengan supir, “Suddah llama djjadi taksi online, Mass?” Yang membuat kami terkekeh ialah kalimatnya yang dibuat-buat menyerupai logat Jawa. “Baru 2 minggu, Mas.” Dalam pendengaran saya pelafalannya begini, “Baroe doea minggoe, Masse.”
Malioboro memulai keruwetan kami. Malioboro tak seperti yang saya bayangkan: jalanan dan pedestrian asri nan estetik dengan kiri-kanan penuh bunga, senyum orang-orang dan udara yang mengalun lembut. Jalanan dipenuhi kendaraan, juga sado dan becak. Sepanjang pedestrian pedagang kaki lima berjejer menjual entah apa saja. Lain lagi pedagang kaki seribu (tak capek-capek kesana kemari) yang hilir mudik menawarkan dagangan. Yang ditawarkan aneh. Boneka kayu pengusir semut? Gantungan jilbab? Alat penggaruk? Kacamata baca? Tolong jelaskan di kolom komentar tulisan ini, apa fungsi alat tersebut bagi pengunjung seperti kami.
Baca juga: Mengalami sesuatu yang tidak dipercaya
Spirit pedagang kaki seribu kan maen! Berulang menawarkan dagangan yang sama tepat ke moncong hidung kami. Tak peduli dan tak punya empati kepada kami yang menderita semalaman di bus yang mengeluarkan isi perut dua perempuan yang kami bawa, Ini membuat saya dan Mulya segera bangkit mencari kost di wilayah lorong-lorong Maliboro tersebut.
Kami memasuki lorong terdekat, dan betapa uniknya di sepanjang lorong tersebut barang yang dijual ialah benda pecah belah yang terbuat dari berbagai jenis perak, metal, kuningan, ah pokoknya segala jenis logam. “Serasa memasuki Diagon Alley,” saya mengucap lirih. Bukannya menemukan kost, kami justru menemukan Jalan Mataram dengan hotel mewah di depannya.
Kami bertanya kepada warga sekitar. “Ora, ora!” Cuma itu yang kami dapat. Berkeliling nyaris satu jam memuntahkan kami kembali ke Malioboro.
Di pikiran saya cuma satu. Betapa kesalnya kedua perempuan yang menunggu kami, dan membawa hasil yang nihil. Keduanya sayu. “Sarapanlah kalian dulu,” ujar Ibu saya. Mulya dan istrinya pergi ke arah 0 KM Jogja. Saya tak selera makan. Meski perut keroncongan dan sehabis berjalan keliling satu jam. Tak ada makanan yang sesuai. Saya lihat-lihat lagi manatahu bisa membetikkan selera.
Saya lihat sate udang. Harganya tertera di pamflet Rp 25 ribu. Busyet! Akhirnya, saat itu saya hanya mampu menelan satu menu yang bagi saya normal: telor gulung.
Putus harapan di antara tumpukan tas, saya dan ibu melihat bus Damri berlabel “Candi Borobudur-Malioboro” melintas santuy. Ibu mengusulkan agar kami langsung ke Borobudur saja dan mencari penginapan disana. Saya refleks membuka Google mencari halte atau tempat pemberangkatan bus tersebut. Grand Inna Hotel! Jaraknya 850 meter dari posisi kami.
850 meter adalah jarak yang dekat apabila kita melangkah tanpa membawa beban tas berat plus beban tak tidur bahkan muntah kayak di bus. Kami terseok-seok seperti US Army pulang perang. Di setiap 50 meter terdapat petugas: Satgas Covid, polisi, anggota LSM, dan entah apa pun yang berseragam sibuk merazia masker.
Baca juga: Vaksin dan imajinasi yang bikin ngeri
Saya dengan keringat yang berlumuran menggandeng tas berat kiri-kanan, bertanya kepada setiap dari mereka, “Di mana saya bisa mendapatkan bus Damri ke Borobudur?” Pertanyaan saya dijawab berbagai kemungkinan: ada yang bilang ke sana, ke sini, ke sono, ke sane! Intinya tak seorang pun petugas itu tahu di mana letak halte Damri.
Ibu saya, Mulya dan istrinya menyerah di batas 700 meter. Saya memutuskan terus bergerak hingga Grand Inna Hotel, dan menemukan kesia-siaan. Tak ada apa pun di sana. Saya coba terus berjalan bahkan hingga belokan ke arah stasiun. Nihil! Saya berbalik, dan memasuk halaman Grand Inna Hotel. Satpamnya celingak-celinguk, “Dimana saya bisa mendapatkan bus Damri ke Borobudur?” Saya mengulang pertanyaan yang sama untuk ke-17 kalinya.
“Ooooooouuu, ndak di sini, Mas. Damri ke Borobudur adanya dari Hotel Limaran.”
“Google keparat!” umpat saya dalam hati.
“Nggaaa jauh kok, Mas. Dari sini naik beccak sajja.”
“Saya cek di Google, katanya haltenya di sini.”
“Oooooiyoo, Mas. Dullu haltenya di sini, tapi ndak ada penumpang, jadi wes pindah.”
“Google keparat!” umpat saya sekali lagi.
Maka, dengan muka masam bak asam sulfat, kami berempat menaiki dua becak. Ketiganya tentu kesal dengan saya, meskipun sepenuhnya bukan salah saya. Ongkos tiap becak 25 ribu untuk jarak 1,2 km terpaksa direlakan. Saya perhatikan, supir-supir sado sepanjang Malioboro termangu, acuh dan sinis. Tak mengesankan keramahan. Saya berprasangka barangkali efek dari pandemi yang mengganggu pendapatan harian mereka.
Begitu hendak turun dari becak, bus Damri dengan santuy memasuki halaman Hotel Limaran. Ini melegakan hati saya. Saya masuk ke lobi hotel dan diarahkan ke meja luar, “Ke Borobudur (?)” kalimat saya bernada pertanyaan entah pernyataan. Lelaki kurus di depan saya mengangguk santuy dengan menggoreskan senyum mayun. “Rp 25 ribu,” ujarnya ketika saya tanya ongkos. “Bukannya 20 ribu?” karena di Google saya cek memang 20 ribu. Lelaki Lelaki kurus di depan saya menggeleng santuy dengan menggoreskan senyum mayun. “Keparat kuadrat buat Google!”
Mungkin sebab terlalu penat dan prihatin melihat istrinya, Mulya diam-diam memesan kamar di hotel tersebut. 180 ribu permalam. Mereka berdua naik ke atas dan turun kembali tanpa barang-barang. “Nanti sore kami balik kesini, lagi. Kalian cari penginapan di Borobudur kan?” Saya mengangguk tak yakin.
Berangkatlah bus Damri menuju Borobudur. Busnya nyaman sepadan dengan supirnya yang ramah. Sepanjang jalan 40 km itu saya mencoba tidur, dan tak berhasil akibat percakapan ibu saya dengan supir tanpa jeda berarti. Tibalah di pangkalan Damri Borobudur, tepat di depan warung mi ayam. Kami memesan makan. Pak Supir turut memasuki warung, dan berkata pada Ibu saya, “Ini loh, Bu. Ibu warung ini punya penginapan murah di belakang.” Ibu saya menengok ke belakang dan sepakat 200 ribu untuk tiga hari (walau sebenarnya bila dihitung berdasarkan jadwal check-in/out hotel itu sama dengan dua hari).
Setelah meletakkan barang, kami bergegas ke Borobodur. Sebab Mulya dan istrinya mesti kembali naik bus Damri pukul lima sore nanti. Di gerbang depan halaman Borobudur, petugas menjawab, “Rp 50 ribu perorang,” untuk pertanyaan harga tiket masuk. Saya dan Ibu mengurungkan niat. “Besok pagi sajalah kita masuk,” ujar Ibu saya. Mulya dan istrinya sajalah yang masuk.
Saya dan Ibu berkeliling di halaman luar bagian dari Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu. Ibu membeli es cendol, yang rasanya asin sekali. Kami tak luput menjadi sasaran pedagang kaki seribu. Spirit yang sama di Malioboro saya temukan kembali. Spirit yang lama-kelamaan justru memancing emosi. Mereka silih berganti menyapa kami, dengan kalimat jurus “Bagi-bagi rezeki” dan harganya yang murah untuk pembelian beberapa barang sekaligus.
Ibu saya tak tahan, dan membeli dua dompet seharga 20 ribu. Saya akui dompet tersebut memang indah. Sayang saya sedang tak punya pacar untuk saya berikan. Tak selesai di situ, Ibu kembali tergoda melihat tas bertuliskan “Yogyakarta” dengan font mirip Monotype Corsiva. Ibu membeli 2 tas sekaligus. Saku saya tak keberatan mengeluarkan 120 ribu. Saya pikir tak apalah. Kenang-kenangan dari Borobudur. Saya sendiri tak punya rencana membeli apa pun.
Seraya menunggu Mulya dan istrinya keluar dari Borobudur, kami duduk di rerumputan dan kembali menjadi sasaran pedagang kaki seribu. Pedagang tak cuma orang orang muda. Nenek-nenek pun tak mau ketinggalan ambil andil. Saya berpikir, “Ini mana anak-cucunya, ya. Kok tega sekali!” Kesal dihantam spirit pedagang yang silih berganti tak kenal lelah, saya dan ibu memutuskan kembali duluan ke penginapan.
Tiba di kasur saya langsung tertidur. Ketika terbangun hari sudah gelap. Notifikasi dari Mulya, “Kami langsung pulang ya. Makasih banyak Kal, sampai ketemu lagi.” Dilengkapi emoticon tangan mengatup.
Malam itu saya tak sanggup lagi keluar. Ibu saya pergi membeli nasi padang (satu-satunya makanan yang bisa kami telan dengan sempurna selama di Jawa) dan 10 air mineral gelas. “Pasar malam di luar, Kal! Ramai sekali!” Nada Ibu gembira seperti mengabarkan kemerdekaan. Saya cuma bisa terdiam, seraya menyantap nasi padang lamat-lamat.
Esok harinya, pagi hingga sore, saya yang memang tak berniat masuk ke Borobudur cuma golek-golek di kasur. Malamnya, saya penasaran membuktikan kabar keramaian yang dikatakan Ibu saya.
Baca juga: Mengapa kita harus pintar?
Kami turun dari penginapan dan mencari nasi goreng. Tak terlalu ramai saya perhatikan. Sepanjang pedestrian berjejer jajanan. Kami berjalan ke arah utara, dan menemukan cafe yang menyediakan balkon. Sebelum naik saya cek harga. Aman. Kami pesan dua porsi nasi goreng plus sphagetti sebagai tambahan.
Suasana dari atas balkon tenang sekali. Nyaris tak ada suara, apalagi klakson. Jejeran jajanan di bawah memanggil-manggil saya untuk segera dibeli. Mendadak mati lampu. Tak lama. Tapi cukup membuat prihatin: di Borobudur, salah satu warisan dunia ini bisa mati lampu. Saya membayangkan alangkah gelapnya Borobudur di malam hari. Saya membayangkan berbagai makhluk gaib––seperti Dementor dari Azkaban––meronda di sekeliling stupa-stupa.
Lampu hidup dan kami bergegas turun ke pedestrian. Saya pesan pizza, dimsum, bakso, dan greentea milk. Perut saya benar-benar padat. Membuat saya tak bisa lekas tidur.
Esok siangnya, kami menumpang Damri dengan supir yang sama. Kali ini saya duduk di depan. Awal perjalanan dimulai dengan santai. Armada busnya memang nyaman. Sepertiga jalan pak supir memulai cerita yang tak begitu menarik. Saya––sebagai seorang pelajar sekaligus mengorek informasi Jogja sebagai “kota pelajar”––mengarahkan cerita tentang pendidikan.
“Anak saya sudah semester 11, Mas.” Ada dua nada dalam kalimat itu, sedih dan bangga. Sedih karena anaknya tak kunjung wisuda. Bangga sebab anaknya berbeda, melampaui batas normal. Saya tak begitu kaget. Beberapa teman saya bernasib sama.
“Uang kuliahnya Rp 6,3 juta persemester.” Alamak, itu setara biaya S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Sumatera Utara, yang saya tak berani mengambilnya. “Beruntung sekarang dia sudah kerja bantu-bantu teman, jadi uang kuliah semester ini sudah tanggung sendiri.” Ternyata persoalan belum selesai, “Ya, anak saya yang kedua baru masuk kuliah juga di UNY. Rp 3,8 juta persemester.” Saya sebagai seorang penerima beasiswa cuma bisa tersenyum getir.
Menariknya ada quote yang saya telisik dari pak supir tersebut, “Kalau kita memudahkan orang lain, maka orang lain akan memudahkan kita.” Wait a second, bukankah itu quote yang pernah diucapkan Mulya Jamil ketika ia akan dimutasi ke kantor cabang Banda Aceh? Entahlah, sampai sekarang saya tak bisa menebak, siapa yang menciptakan quote tersebut.
Baca juga: Realitas beauty privilege di masyarakat
Kami turun di halte depan Taman Pintar. Menunggu TransJogja. Tarifnya Rp 3500 jauh-dekat. Perjalanan lancar jaya hingga tiba di Giwangan yang senyap. Melihat kami membawa beban tas, tiga agen bus menyambut kami. “Bandung? Rp 165 ribu, Mas.” Saya langsung menyahut, “Tak usah pakai makan.”
Maka dipesanlah dua tiket 150 ribu untuk keberangkatan pukul 15.30 dengan bus Rajawali. Waktu bergulir, bus tak tampak juga. Hari menggelap jelang maghrib. Saya setengah mati menahan diri untuk tak emosi kepada agen bus yang sudah tua. Ibu saya berulangkali coba bertanya. Di pikiran saya cuma satu, “Mungkin kami sudah kena tipu!? Orang Medan kena tipu memalukan sekali,” pikir saya.
Ibu juga sudah berulangkali ke WC Umum (tapi bayar). Saat terakhir, Ibu saya menyerahkan uang logam seribu, si Toilet Keeper langsung protes, “Kan bukan salah saya busnya terlambat. Harus tetap dua ribu!” tegasnya. Beruntung Ibu saya tak memakinya.
Akhirnya seorang agen lain (agaknya resmi) memberi kami tiket lainnya berlabel Rajawali, dan menyatakan bus akan segera tiba dan langsung berangkat. Di tiket yang baru harganya yang tertera Rp 135 ribu. Awalnya saya diam. Tapi saat ke orang lain yang baru datang ingin membeli tiket, dia mengatakan harga tiket hanya Rp 125 ribu, sontak saya protes. “Lah, itu kan Mas-nya beli tiket dari agen. Harusnya Mas beli langsung ke saya.”
Bus Rajawali silver berbadan lebar tiba, dan setelah kami menaikinya langsung segera berangkat. Syukurlah bus ini nyaman dan longgar. Hanya berisi selusin penumpang. Kami menelan Antimo dan tertidur hingga bus berhenti dan sampai.
“Begitulah Jogja, begitulah kota yang selalu diidam-idamkan orang untuk dikunjungi, begitulah adanya, cukuplah saya yang ke sana, dan biarlah ekspektasi orang-orang tentang Jogja hidup dalam kepala mereka selamanya,” igau saya sebelum tidur.(*)
Baca juga: